Petang itu mata dan pikiranku kupaksa fokus mengikuti Zoom meeting lintas benua tentang COP30. Kali ini, para pembicara berasal dari Brasil, negara yang pada 10-21 November 2025 ini bakal menjadi tuan rumah Conference of the Parties (COP) ke-30. Sebuah forum global tertinggi soal perubahan iklim di bawah PBB.
Sesi itu awalnya terdengar akademis, penuh istilah asing seperti NDCs, carbon offset, dan Baku–Belém Roadmap. Tapi pelan-pelan, aku tersadar. Pembicaraan itu bukan cuma milik diplomat di ruang konferensi.
Ini tentang aku, tentang kalian, dan tentang rumah yang kita pijak, bumi.
Antara Amazon dan Nusantara: Dua Paru Dunia yang Bernapas Sama
 |
| Hutan Adat di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya ⓒ Konservasi Indonesia |
Ada yang menarik dari lokasi gelaran COP30. Pertemuan bergengsi ini akan digelar di Belém, Brasil. Sekadar informasi, Belém adalah kota yang berdiri di gerbang hutan Amazon, sang paru-paru dunia yang kini menipis napasnya akibat deforestasi. Tapi dalam refleksi pribadiku sebagai bagian dari ECO Blogger Squad sejak 2021, aku merasa kisah itu tak jauh berbeda dengan Indonesia.
Brasil dan Indonesia seperti dua entitas yang kembar ekologi.
Dua negara berkembang ini sama-sama punya hutan tropis luas, biodiversitas tinggi, tapi juga sama-sama terluka oleh tambang, sawit, dan ambisi ekonomi. Dalam sesi itu, Cinthia Leone, Climate Diplomacy Coordinator dari ClimaInfo, berkata:
“Krisis iklim bukan hanya soal data, tapi juga soal imajinasi dan komunikasi.”
Kalimat itu begitu menghentak pikiranku.
 |
| Obrolan COP30 bersama EBS dan aktivis lingkungan Brazil |
Karena iya, krisis iklim bukan sekadar angka di laporan PBB semata, tapi tentang petani di Jawa yang gagal panen karena cuaca ekstrem, nelayan pesisir kehilangan rumah karena laut naik, atau masyarakat adat di Kalimantan yang harus berhadapan dengan korporasi demi mempertahankan tanahnya.
Di Brasil, masyarakat adat Amazon juga menghadapi ancaman yang sama. Mereka menjaga hutan demi dunia, tapi malah dikriminalisasi.
Hal serupa juga terjadi di Indonesia. Data dari AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) menunjukkan, sepanjang 2023–2024 ada lebih dari 100 kasus kriminalisasi masyarakat adat terkait konflik lahan dan lingkungan. Padahal, laporan UNDP (United Nations Development Programme) menegaskan bahwa kawasan hutan yang dikelola masyarakat adat justru menyimpan cadangan karbon paling tinggi dan paling stabil di dunia.
Artinya, keadilan iklim tak bisa lepas dari keadilan sosial. Kita tak bisa bicara COP30 tanpa menyinggung mereka yang paling menjaga, tapi paling sering terluka.
Melawan Hoaks, Menyuarakan Harapan
Pertemuan online lintas negara ini semakin menarik saat Thais Lazzeri, pendiri media FALA di Brasil mulai bercerita. Ia menyebut bahwa menjelang COP30, dunia sedang menghadapi disinformasi iklim. Apa itu? Sebuah gelombang hoaks yang menyesatkan publik soal isu lingkungan.
“Kebohongan menyebar 70% lebih cepat daripada kebenaran,” kata Lazzeri penuh semangat dalam bahasa Portugis.
Dan data itu nyata.
Di Brasil, lebih dari 30% postingan viral tentang COP30 ternyata berisi hoaks. Mulai dari teori konspirasi bahwa perubahan iklim cuma agenda elit global, sampai klaim palsu yang memengaruhi kebijakan nasional.
Aaah, ini membuatku teringat film DON’T LOOK UP (2021). Di mana para pejabat menertawakan ilmuwan yang berusaha memperingatkan bencana. Dunia nyaris kiamat, tapi semua sibuk dengan ego dan algoritma. Begitulah realita kita hari ini saat kebenaran kalah cepat dari kebohongan yang dikemas cantik.
Sebagai blogger lingkungan yang hobi traveling dan juga seorang scriptwriter, aku jadi semakin yakin. Bahwa perang melawan krisis iklim bukan cuma di lapangan, tapi juga di layar. Menulis, memverifikasi, dan berbagi informasi yang benar adalah bentuk perlawanan kecil yang bisa dilakukan siapa pun.
Dalam obrolan itu, Rafael de Pino, jurnalis dan manajer proyek FALA, juga menekankan pentingnya jurnalisme berbasis komunitas untuk melawan hoaks. Bukan dengan amarah, tapi dengan fakta dan empati. Karena tanpa kita sadari, disinformasi tumbuh subur di ruang yang sunyi.
Ruang di mana kebenaran berhenti disuarakan.
Ruang di mana kebenaran berhenti disuarakan.
Dari Belém ke Nusantara: Cerita yang Senada
 |
| Logo COP30 di Brasilia, Brazil ⓒ Evaristo Sa/AFP |
Ketika dunia bersiap menuju COP30, aku membayangkan momen itu seperti babak kedua film tentang bumi. Dalam penulisan skenario, sekuens dua sebuah cerita biasanya berisi puncak konflik. Di mana ada ketegangan, ada harapan, dan ada suara-suara kecil yang akhirnya mulai didengar.
Aku percaya, kita semua memiliki peran. Entah lewat tulisan, foto, atau percakapan sederhana, kita bisa menjaga kebenaran tetap hidup. Karena bumi tak butuh penyelamat.
Ia butuh pendengar yang jujur dan penutur yang setia.
Seperti kata petuah dalam bahasa Brasil yang sangat kuingat: “A COP é um marco, não o fim.”
COP adalah tonggak, bukan akhir.
Jadi, saat dunia nanti berkumpul di Belém bulan depan, semoga dari Indonesia pun bergema suara yang sama. Bahwa kita masih peduli, masih berjuang, dan masih menulis untuk bumi.
Dengan kata, dengan kebenaran, dan dengan cinta.


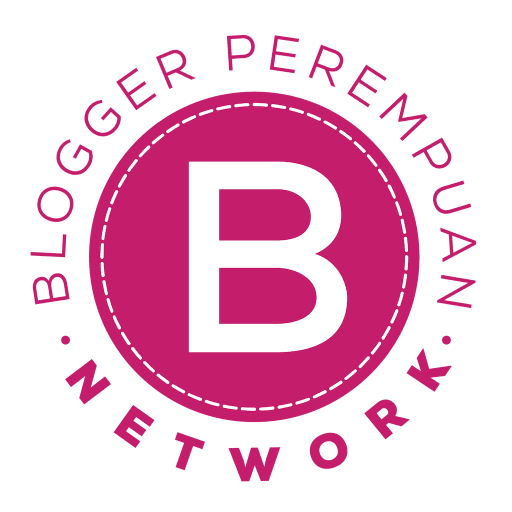



0 تعليقات